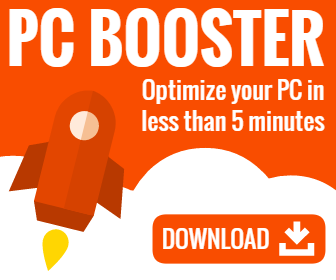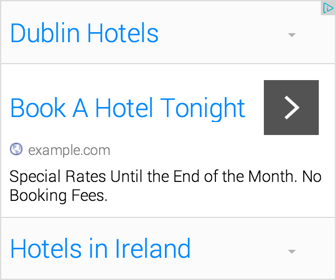INEWSFAKTA.COM | Jakarta, 16-2-2026 – Benarkah oligarki yang merusak tatanan negara Indonesia ? Pertanyaan ini kerap muncul setiap kali publik menyaksikan kebijakan yang terasa jauh dari kepentingan rakyat. Namun, sebagian pengamat menilai, persoalannya tak sesederhana menunjuk segelintir elite ekonomi atau politik. Yang lebih dalam dan lebih sunyi adalah sistem yang sejak lama dibentuk, dilegalkan, dan dibiarkan berjalan dengan logika transaksional.
Dalam sistem seperti itu, kecenderungan buruk tak lagi dianggap penyimpangan—melainkan kewajaran. Politik menjadi arena tawar-menawar kepentingan. Regulasi disusun dalam ruang-ruang kompromi yang tak selalu berpihak pada kepentingan umum. Di titik ini, oligarki bukan sekadar aktor, melainkan gejala dari struktur yang membuka ruang bagi dominasi modal atas kebijakan.
Sejumlah studi menyebut oligarki sebagai konsentrasi kekuasaan ekonomi yang mampu mempengaruhi proses politik dan hukum. Namun dalam konteks Indonesia, pertanyaan krusialnya bukan hanya siapa yang berkuasa, melainkan bagaimana sistem memungkinkan kekuasaan itu bertahan.
Konstitusi Indonesia sejatinya telah memberi arah. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 ayat (2) menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pasal 33 ayat (3) menyebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Secara normatif, arah itu diperkuat oleh Pancasila sebagai dasar negara. Sila kelima berbunyi: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini bukan sekadar frasa simbolik. Ia adalah mandat etis dan konstitusional agar kebijakan publik tidak tersandera oleh kepentingan sempit.
Namun di lapangan, realitas sering kali bergerak berbeda. Praktik politik biaya tinggi, ketergantungan pada sponsor ekonomi, hingga relasi kuasa antara pengusaha dan pejabat publik membentuk pola yang sulit diputus. Ketika transaksi menjadi fondasi, integritas menjadi variabel yang mudah dinegosiasikan.
“ Sudah masuk sistem korup, baru paham ”, ujar seorang mantan pejabat yang enggan disebut namanya. Ia mengakui bahwa banyak keputusan strategis tak lepas dari tekanan politik dan ekonomi. “Perbaikannya tidak mudah, bahkan terasa mustahil jika hanya mengandalkan individu.”
Pandangan ini menggarisbawahi satu hal: persoalan bukan semata moral personal, melainkan desain kelembagaan. Jika mekanisme pembiayaan politik tidak transparan, jika pengawasan lemah, dan jika penegakan hukum tumpul ke atas, maka oligarki menemukan ruang hidupnya.
Pertanyaannya kemudian : di mana UUD 1945 dan Pancasila ?
Secara hukum, keduanya tetap berdiri sebagai fondasi. Tetapi dalam praktik, implementasi nilai-nilainya kerap tersubordinasi oleh realitas kekuasaan. Demokrasi prosedural berjalan—pemilu dilaksanakan, lembaga negara berfungsi—namun substansi keadilan sosial dan kedaulatan rakyat dipertanyakan.
Reformasi struktural menjadi kata kunci yang berulang disebut, tetapi jarang tuntas diwujudkan. Transparansi pembiayaan politik, pembatasan konflik kepentingan, penguatan lembaga pengawas, serta konsistensi penegakan hukum adalah prasyarat minimal. Tanpa itu, sistem yang telah dilegalkan akan terus memproduksi pola lama.
Menuding oligarki mungkin memberi rasa kejelasan. Namun membenahi sistem menuntut keberanian kolektif—dari pembuat kebijakan, penegak hukum, hingga masyarakat sipil. Konstitusi telah memberi arah. Ideologi negara telah memberi nilai.
Tinggal satu pertanyaan yang belum terjawab sepenuhnya : apakah bangsa ini masih mau kembali menjadikan UUD 1945 dan Pancasila sebagai pedoman nyata, bukan sekadar kutipan dalam pidato ?
1 karya jurnalis dari H.Bataya sebagai upaya edukasi warga dan tanggungjawab sebagai ketua Yayasan Karya Peduli Warga (www.karyapeduli.com) di bidang sosial dan kemanusiaan yang bersumber dari pengamatan dan pelayanan sosial ditambah studi literasi. Bila ada masukan, sanggahan atau koreksi , silahkan menghubungi redaksi untuk perbaikan.
(Red/HB)