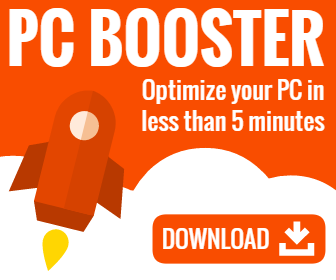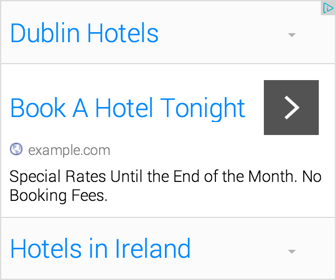INEWSFAKTA.COM | Jakarta, 11-1-2026 – Negara akhirnya menuliskan kewajiban yang selama ini hanya menjadi beban moral warga : melapor. Pasal 23 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menegaskan, setiap orang yang mengetahui adanya permufakatan jahat wajib segera melaporkannya kepada penyelidik atau penyidik.
Rumusan ini tampak tegas. Bahkan rinci. Laporan harus dicatat, ditandatangani, dan diberi tanda terima. Bila laporan disampaikan secara lisan, penyidik wajib menuangkannya dalam berita acara. Bila pelapor tak bisa membaca atau menulis, keadaan itu pun harus dicatat. Secara normatif, negara terlihat ingin memastikan bahwa setiap aduan warga diakui secara administratif.
Empat Belas Hari yang Sering Menguap
Ayat (6) Pasal 23 memuat tenggat waktu yang selama ini kerap dipersoalkan publik : penyidik atau penyelidik wajib menanggapi laporan dalam waktu paling lama 14 hari. Jika tidak, pelapor berhak melaporkan penyidik yang diam kepada atasan atau pejabat pengawas.
Secara teoritis, ini adalah kemajuan. Untuk pertama kalinya, kelambanan aparat diberi batas waktu eksplisit. Tetapi praktik penegakan hukum menunjukkan kenyataan yang berulang: laporan diterima, nomor registrasi diberikan, lalu proses berhenti di meja administrasi.
Laporan dugaan korupsi, penyalahgunaan wewenang, kejahatan struktural, hingga kejahatan korporasi sering kali “mengendap”. Tak jarang, pelapor dipanggil bukan untuk klarifikasi substansi perkara, melainkan untuk dimintai keterangan tambahan yang berujung tanpa kepastian.
Empat belas hari berlalu tanpa respons substantif. Dan di titik itu, keberanian warga mulai diuji.
Beban Berlapis di Pundak Pelapor
Pasal ini secara tidak langsung memindahkan sebagian beban penegakan hukum ke warga. Warga wajib melapor. Warga wajib menandatangani. Warga wajib menunggu. Bahkan ketika aparat tidak bertindak, warga kembali dibebani kewajiban baru : melaporkan aparat yang diam.
Di atas kertas, mekanisme ini disebut sebagai check and balance. Dalam praktik, ia sering berubah menjadi lingkaran administratif yang melelahkan. Pelapor menghadapi risiko sosial, psikologis, bahkan hukum—tanpa jaminan bahwa laporannya benar-benar diproses.
Fakta di lapangan menunjukkan, tidak sedikit pelapor justru berakhir sebagai pihak yang diperiksa berulang kali, sementara terlapor tetap berada di posisi aman. Negara meminta keberanian warga, tetapi belum sepenuhnya menyiapkan perlindungan yang sepadan.
Sanksi yang Ada, Tapi Jarang Terlihat
Ayat (7) Pasal 23 mengatur sanksi bagi penyidik atau penyelidik yang melampaui kewenangan, melanggar hukum, atau kode etik. Sanksinya berlapis: administratif, etik, hingga pidana.
Masalahnya bukan pada ketiadaan norma, melainkan pada konsistensi penerapan. Sepanjang sejarah penegakan hukum, sanksi terhadap aparat lebih sering berhenti pada level etik internal. Prosesnya tertutup, hasilnya minim transparansi, dan jarang menyentuh akar masalah: pembiaran terhadap laporan masyarakat.
Tanpa akuntabilitas terbuka, sanksi menjadi pasal yang hidup di undang-undang, tetapi mati di lapangan.
Antara Partisipasi Publik dan Tanggung Jawab Negara
Pasal 23 KUHAP mencerminkan satu pesan penting: negara ingin melibatkan warga dalam pencegahan kejahatan sejak dini. Namun partisipasi publik tidak bisa berdiri sendiri. Ia harus ditopang oleh aparat yang responsif, sistem pengawasan yang nyata, dan perlindungan yang konkret bagi pelapor.
Tanpa itu, kewajiban melapor berisiko berubah menjadi formalitas hukum yang timpang. Negara menuntut keberanian, tetapi belum sepenuhnya menunaikan tanggung jawabnya.
Keluhan masyarakat tidak berhenti pada lambannya penyidik. Sorotan juga mengarah ke badan-badan pengawas yang secara normatif diberi mandat mengawasi jalannya penegakan hukum. Dalam banyak aduan publik, lembaga pengawasan justru dipersepsikan tidak hadir secara fungsional. Alih-alih melakukan pemeriksaan substantif, memanggil pihak terkait, atau membuka hasil pengawasan ke publik, sebagian pengawas lebih sering muncul di ruang digital—memproduksi konten seremonial, unggahan media sosial, dan aktivitas simbolik. Di tengah laporan yang menumpuk dan perkara yang tak bergerak, publik sinis menyebut pengawasan hukum hari ini sebatas “tiktok-an”: ramai di layar, senyap di lapangan. Akibatnya, mekanisme pengaduan berlapis yang dijanjikan undang-undang kehilangan makna, karena pengawasan yang seharusnya menjadi rem justru ikut larut dalam budaya pencitraan.
Dalam hukum acara pidana, keadilan bukan hanya soal menerima laporan. Ia tentang memastikan bahwa setiap laporan benar-benar ditindaklanjuti. Bukan sekadar dicatat, diberi tanda terima, lalu dilupakan.
*** Tulisan ini bertujuan edukasi warga negara dan perbaikan pemerintahan, bila ada koreksi, sanggahan, klarifikasi , silahkan menghubungi redaksi untuk perbaikan.
(Red/HB)