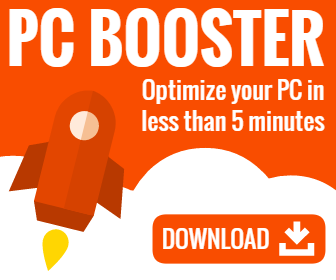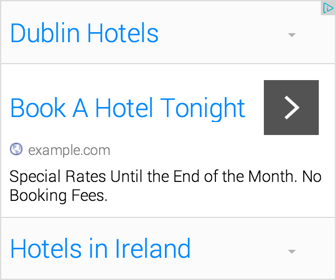INEWSFAKTA.COM | Jakarta, 1-2-2026 – Ditengah konflik pengelolaan rumah susun, satu fakta kerap diabaikan : warga bukan sekadar penghuni atau konsumen. Mereka juga memiliki fungsi pengawasan. Hak untuk mengawasi, meminta klarifikasi, dan melaporkan penyimpangan melekat pada warga sebagai subjek hukum—bukan sebagai pihak yang harus diam.
Namun, dalam banyak kasus rumah susun di Indonesia, fungsi pengawasan warga justru diposisikan sebagai ancaman. Warga yang bertanya dicurigai, yang melapor dicap provokator, dan yang mengorganisasi aspirasi kolektif dituduh mengganggu ketertiban. Di titik inilah narasi provokator maling dan praktik politik ruang gelap bertemu.
Warga sebagai Pengawas yang Sah
Secara prinsip, pengelolaan hunian vertikal berada di ruang publik terbatas—mengelola dana bersama, fasilitas bersama, dan kepentingan kolektif. Karena itu, warga memiliki hak untuk mengawasi: dari laporan keuangan, kebijakan operasional, hingga kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Pengawasan warga bukan tindakan subversif. Ia adalah mekanisme koreksi. Ketika negara tidak hadir atau pengawasan formal melemah, warga justru menjadi lapis pengaman terakhir untuk mencegah penyimpangan.
Namun, hak ini sering kali dibenturkan dengan tembok administrasi. Informasi dipersulit, rapat dibatasi, dan kebijakan diumumkan sepihak. Setiap upaya membuka informasi dianggap sebagai provokasi.
Pelatihan dalam Ruang Gelap
Di balik penolakan terhadap pengawasan warga, pegiat hunian melihat pola yang berulang. Praktik pengelolaan dalam ruang gelap menciptakan kebiasaan—bahkan semacam “pelatihan”—yang menjauhkan pengelola dari akuntabilitas.
Pola itu antara lain :
* membodohi warga melalui bahasa administratif yang menyesatkan,
* mengaburkan dasar hukum kebijakan,
* dan menormalisasi keputusan yang bertentangan dengan kepatutan.
Dalam kondisi ini, manipulasi bukan lagi penyimpangan sesaat, melainkan metode kerja. Ketika praktik semacam itu dilakukan terus-menerus, pelakunya tidak sekadar melanggar aturan, tetapi juga mengabaikan suara hati dan tanggung jawab moral.
Kehilangan Dimensi Kemanusiaan
Seorang pegiat warga menyebut, praktik yang melawan nurani—membodohi, menekan, dan memutarbalikkan fakta—adalah bentuk kehilangan kemanusiaan dalam pelayanan publik. Pernyataan tersebut bukan ditujukan sebagai penghinaan personal, melainkan kritik keras terhadap perilaku yang menanggalkan etika dasar manusia : kejujuran, empati, dan tanggung jawab.
Dalam perspektif ini, penyebutan provokator maling tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat individu, melainkan untuk menamai praktik provokasi bermotif keuntungan yang bersembunyi di balik administrasi dan otoritas. Provokasi yang menciptakan konflik agar ruang gelap tetap terjaga.
Politik Ruang Gelap Melawan Pengawasan
Politik ruang gelap bekerja dengan satu prinsip: jangan biarkan cahaya masuk. Transparansi dianggap ancaman. Pengawasan dipersepsikan sebagai serangan. Karena itu, warga yang menjalankan fungsi pengawas harus dilabeli agar suaranya kehilangan legitimasi.
Di sinilah stigma provokator—atau tuduhan provokator—digunakan sebagai alat bungkam. Ia memindahkan fokus dari substansi pelanggaran ke perilaku warga. Yang dipersoalkan bukan kebijakan bermasalah, melainkan keberanian warga mempertanyakannya.
Membalik Narasi
Jika warga yang mengawasi disebut provokator, maka perlu dibalik pertanyaannya: siapa yang sesungguhnya memprovokasi konflik? Mereka yang menuntut keterbukaan, atau mereka yang mempertahankan kegelapan?
Dalam konteks rumah susun, provokasi sejati adalah tindakan yang memicu kerugian kolektif melalui kebijakan sepihak, manipulasi, dan penolakan terhadap pengawasan. Selama praktik ini dilindungi oleh ruang gelap dan lemahnya pengawasan negara, konflik akan terus berulang—dan warga akan terus diposisikan sebagai masalah.
Padahal, tanpa warga yang berani mengawasi dan melapor, kegelapan justru akan menjadi norma.
BOX INVESTIGASI | Apa Itu Politik Ruang Gelap?
Politik ruang gelap adalah praktik pengambilan keputusan dan pengelolaan kebijakan yang sengaja dijauhkan dari transparansi, partisipasi publik, dan pengawasan. Ia bekerja dalam keterbatasan informasi, kerancuan aturan, serta relasi informal antar-aktor yang sulit ditelusuri secara terbuka.
Dalam konteks rumah susun, politik ruang gelap muncul ketika :
* keputusan pengelolaan dibuat tanpa melibatkan warga,
* laporan keuangan tidak dibuka atau dipersulit aksesnya,
* kebijakan sepihak diterapkan tanpa dasar hukum yang jelas,
* dan pengawasan negara melemah atau dibiarkan tidak bekerja.
Ruang gelap ini bukan kebetulan, melainkan kondisi yang dipelihara. Dalam kegelapan, praktik penyimpangan lebih mudah dilakukan dan lebih sulit dibuktikan. “Dalam kegelapan, maling beroperasi,” kata seorang pegiat warga. Ketika cahaya transparansi dimatikan, manipulasi administratif, konflik kepentingan, dan perampasan hak dapat berjalan tanpa koreksi.
Politik ruang gelap juga berfungsi sebagai alat pembalik narasi. Kritik warga yang berupaya membuka ruang terang justru dicap sebagai provokasi. Transparansi dianggap ancaman, sementara ketertutupan dijual sebagai stabilitas.
Akibatnya, konflik di rumah susun tidak pernah diselesaikan di akar persoalan. Ia dikelola, dipadamkan sesaat, lalu dibiarkan berulang. Selama ruang gelap tetap dipertahankan, praktik provokator maling—yakni provokasi bermotif keuntungan yang bersembunyi di balik administrasi dan otoritas—akan terus menemukan tempatnya.
*** Tulisan ini bertujuan edukasi warga negara dan perbaikan pemerintahan, bila ada koreksi, sanggahan, klarifikasi , silahkan menghubungi redaksi untuk perbaikan.
(Red/HB)